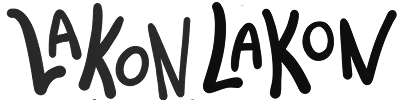oleh Ida Bagus Uttarayana Rake Sandjaja
“Teror”, dari noun menuju verb
Setelah membaca pertama kali lakon bagaimana kalau Munir saja?, seketika keisengan yang pertama kali saya lakukan adalah mencoba memeriksa linimasa peristiwa teror bom yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya pada rentang waktu tahun 2000 sampai dengan 2010 (tahun ketika lakon ini dibuat oleh Ikun SK). Pada rentang tahun tersebut, saya masih duduk di bangku sekolah dasar sampai menengah, dan mencoba memanggil ulang ingatan tentang pemberitaan peristiwa bom yang saya pernah lihat di televisi. Setidaknya pada tahun 2000 saja, terdapat 4 peristiwa teror bom diantaranya; Bom Kedubes Filipina (1 Agustus 2000), Bom Kedubes Malaysia (27 Agustus 2000), Bom Bursa Efek Jakarta (13 September 2000), dan Bom Malam Natal (24 Desember 2000). Menurut sumber wikipedia, total ada 33 korban jiwa, dan ratusan lainnya luka-luka. Rangkaian peristiwa teror bom tersebut seperti semacam “kembang api” sebagai pembuka tahun milenial pada pemerintahan Indonesia di era reformasi.
Mungkin bagi masyarakat Indonesia, dengan segala parameter sudut pandang seperti misalnya distribusi pemberitaan media terkait terorisme, akan dengan mudah menganggap bahwa kata terorisme sering mengacu pada peristiwa teror bom. Tapi Dr. Wening, salah satu karakter utama dalam lakon bagaimana kalau Munir saja? Memiliki argumentasi untuk merespon politik produksi informasi tentang terorisme itu sendiri.
28. Dr. Wening : Maksudku, kamu perlu berhati-hati dengan datamu. Siapa tahu, ada yang sudah tidak adil dalam memproduksi informasi? Kita punya sejarah perang kemerdekaan, di mana para pejuang disebut sebagai ekstrimis dalam bahasa kolonialisme penjajah. Ingat, media tidak pernah netral. Pun, juga bahasa.
Hening sesaat. Keduanya seperti asyik dengan layar-layar laptopnya.
29. Dr. WENING: Tetapi, kalau ukurannya atau identifikasinya memasang dan meledakkan bom, memang sudah bisa. Tetapi kalau ukurannya adalah teror, mungkin ada yang perlu dipercakapkan lebih dulu dalam sebuah permainan bahasa.
Selanjutnya dari potongan dialog di atas, Dr. Wening menambahkan arti kata teror yang didapatnya dari kamus. Sebagai kata benda, teror memiliki arti usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan turunannya sebagai kata kerja, meneror memiliki arti perbuatan kejam (sewenang-wenang, dsb) untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut. Pun yang menarik, jika mengutip dari apa yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), contoh kalimat yang menyertai arti dari kata teror adalah : “mereka meneror rakyat dengan melakukan penculikan dan penangkapan”, terdengar familiar dan cukup kontekstual jika berkaca kepada kondisi politik Indonesia saat ini, dan yang pernah terjadi sepanjang masa pemerintahan Orde Baru (Orba). Mungkin berangkat dari contoh kalimat dari arti kata teror yang ada pada KBBI, menjadi penguat opini personal yang bersifat ideologis yang dimiliki Dr. Wening, dan yang kerap dia diskusikan dengan mahasiswa bimbingannya, Yuda.
Latar Tempat sebagai Konteks Sosial bagaimana kalau Munir saja?
Lakon ini dibuka dengan memposisikan area kampus sebagai titik berangkat perbincangan isu, yaitu halaman kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP). Berangkat dari titimangsa lakon, dan domisili penulis yaitu Yogyakarta, bisa dibayangkan mungkin lakon ini berada pada lingkungan kampus seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), atau UPN Veteran Yogyakarta. Kita tahu bahwa lingkungan kampus menjadi tempat pertukaran pengetahuan dan informasi yang paling bebas dan kritis, dan penulis sangat strategis dalam memilih latar tempat lakon bagaimana kalau Munir saja?. Tidak dipungkiri juga bahwa lingkungan kampus menjadi lahan subur untuk upaya dokstrinisasi, apapun pandangan ideologisnya, baik dari sudut pandang jurusan atau program studi hingga pada bentuk kolektif seperti organisasi mahasiswa.
Diceritakan Yuda sebagai mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi, sedang melakukan bimbingan tesis dengan dosen pembimbingnya, yaitu Dr. Wening. Lakon dibuka dengan adegan Yuda mengiringi Dr.Wening yang sedang mengayuh kursi rodanya, mereka sedang mencari spot yang nyaman seperti sudut taman di pinggiran gedung fakultas. Bisa dibayangkan bahwa suasana kampus yang rindang, seperangkat meja dan kursi taman, akan menjadi saksi bisu perbincangan ringan tentang tesis, tapi sarat atas isu kritis dan berbahaya, hingga konspirasi neokolonialisme.
Lakon bagaimana kalau Munir saja? Memiliki 3 latar tempat yang berbeda; lingkungan kampus, sebuah markas persembunyian, dan teras belakang rumah. Adegan atau babak 1 yang berada dalam lingkungan kampus, menjadi yang paling dominan dalam lakon ini, tentu ini seiring dengan porsi muatan dalam membangun pengembangan premis dan isu yang sedang diperbincangan, adegan 1 sebagai bab “sebab”. Sedangkan adegan 2 dan 3, menjadi bab “akibat”, yang memiliki alur maju setelah linimasa adegan 1.
Pada adegan 2, neben-teks yang tertulis menggambarkan sebuah bar. Dan yang seperti kita tahu, misalnya pada film-film bertema agen rahasia, tempat seperti bar yang memiliki atmosfer yang gelap dan suram, sifat “misterius” dari bar ini menjadi semacam plot-twist dalam lakon bagaimana kalau Munir saja?. Mari kita lihat potongan neben-teks yang menggambarkan latar tempat dari adegan 2.
Ruangan ini terlihat seperti sebuah club dan bar sekaligus. Ada meja bartender, beberapa tempat duduk dan kursi. Panel-panel permainan ketangkasan: papan sasaran lempar anak panah; figur-figur manusia dua dimensi yang bergerak hingga bisa hilang-muncul dari sisi ke sisi layaknya sebuah sasaran latihan menembak yang ada di bibir depan panggung sehingga apabila tembakan meleset secara psikologis akan mengenai penonton; boneka karet setinggi manusia yang biasa digunakan sebagai sasaran pukulan dan mampu bergerak lentur sesuai arah dan kekuatan pemukulnya dalam sebuah latihan tinju. Ada cincin-cincin besi yang digantung untuk berlatih kekuatan lengan sambil berayun-ayun yang biasa dilakukan pesenam tradisional gaya keindahan.
Dengan latar tempat yang digambarkan di atas, bersamaan dengan adegan Yuda yang sedang memukuli boneka ketika Marwan, tokoh laki-laki paruh baya, yang datang juga untuk berlatih di lokasi itu, jelas bahwa Yuda memiliki latar belakang yang spesial, tidak hanya sebagai seorang mahasiswa S2 tingkat akhir semata. Dan masih dalam apa yang bisa dibayangkan bersama dalam kerja-kerja intelegen, ruang seperti ini akan sangat familiar salah satunya sebagai ruang interogasi, atau tempat di mana mendiskusikan strategi yang sangat rahasia. Jika kita menilik laporan-laporan dokumentasi terkait apa yang terjadi dalam kerusuhan 98, atau yang terjadi sepanjang Orde Baru yang dimulai pada tahun 1965, muncul memori kolektif dimana ruang-ruang interogasi untuk menyekap dan menyiksa para aktivis yang berjuang menjadi oposisi pemerintah, hingga beberapa yang menerima nasib naas dan “hilang” sampai sekarang.
Adegan 3 sebagai babak terakhir, pemilihan latar teras belakang rumah, tempat di mana Yuda dan istrinya Jasmine yang sedang mengandung (mungkin anak pertama meraka), sedang duduk santai memperbincangkan pilihan nama untuk jabang bayi mereka. Pemilihan posisi belakang, sebagai posisi teras rumah, menjadi semacam upaya anti-klimaks dalam lakon bagaimana kalau Munir saja?. Teras belakang yang posisinya pasti tertutup dari luar rumah, mempertegas latar belakang Yuda. Yuda tidak hanya sedang menunggu kelahiran anaknya, tapi juga sedang menunggu kabar kematian seseorang yang sangat dia kenal, Dr. Wening.
Politik Bahasa, Ruang, hingga Konspirasi Global
Pada lakon bagaimana kalau Munir saja? akan banyak ditemukan perbincangan tentang bagaimana isu terorisme bergulir dalam sudut pandang yang beragam, khususnya dalam kacamata ilmu komunikasi. Berangkat dari niatan awal Yuda yang sedang melakukan bimbingan rutin dengan Dr. Wening, tesis Yuda menganalisa pemberitaan tentang terorisme, baik secara general yang sering diberitakan di media massa, sampai teori-teori kritis yang tersembunyi di dalam pemberitaan tersebut. Dalam perbincangan awal antara Yuda dan Dr. Wening, terlihat jelas posisi dominasi intelektual antara mahasiswa dan dosennya, Yuda yang terkesan menghadirkan data-data mentah diikuti dengan analasisanya, yang sering direspon dengan argumentasi kritis oleh Dr.Wening.
Pada bagian awal, Dr.Wening seperti sudah mempertanyakan bagaimana Yuda menggunakan frasa “para teroris”, yang menurut Dr.Wening menjadi semacam justfikasi media massa untuk menyebut para pelaku teror bom. Contohnya pada potongan dialog berikut:
Dr. WENING: Maksudnya, apakah mereka itu teroris ataukah mereka dimaklumkan sebagai teroris.
Yuda tertegun. Sejenak. Menatap tajam Doktor Wening. Doktor Wening mengulang pertanyaannya.
Dr. WENING: Apakah mereka itu teroris ataukah mereka dimaklumkan sebagai teroris?
YUDA: Setengahnya, mereka, memang dimaklumkan sebagai teroris. Tetapi,
apakah dengan meledakan bom di beberapa tempat belum bisa digunakan untuk mengindikasikan keberadaan mereka sebagai pencipta teror bagi warga masyarakat?
Mungkin ini yang dimaksud Dr. Wening tentang politik bahasa. Seperti yang kita tahu bersama bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam distribusi informasi, dan pemerintah menjadi seakan harus punya pengaruh dalam mengontrol kebijakan publik. Pada zaman Orba misalnya, Indonesia memiliki Departemen Penerangan Republik Indonesia, yang memilki kontrol kuat dalam memelihara narasi peristiwa 65 dan menjaga konspirasi PKI dan hal-hal yang berbau Komunis sebagai topik haram pada masa itu. Produksi media hiburan seperti film pun tidak lepas sasaran, dan film G30SPKI menjadi satu primadona keberhasilan produk dari Departemen Penerangan zaman Orba.
Selanjutya dari data cuplikan berita yang dimiliki Yuda, Dr. Wening mengelaborasikannya dengan apa yang disebut teror itu sendiri. Diskusi terkait apakah yang hendak melakukan penggerebekan (Densus 88) tidak punya andil sedikitpun dalam menambah kesan teror yang terjadi di sekitar tempat penggerebekan? Pada poin ini, Dr. Wening mengajak kita untuk menarik diri dan “berprasangka”, siapa yang meneror dan siapa yang menjadi korban?
Lebih spesifik lagi, Dr. Wening mengkritik bagaimana media secara serampangan menulis berita tentang teror-teror tersebut. Seringkali baik media dan aparat, yang memiliki peran dalam proses penggerebekan (dan juga pemberitaannya), tidak menyadari efek psikologis publik yang mungkin punya dampak yang beragam. Jika boleh memakai analogi film superhero, pernahkah kita membayangkan gedung-gedung yang hancur dalam proses petarungan antara si pahlawan dan si penjahat, masyarakat sipil yang menjadi korban, jarang mendapatkan sudut pandangnya sendiri tentang kerugian apa yang tidak terlihat dalam kacamata layar.
Menyambung dari pembahasan politik bahasa, dialog-dialog yang terjadi antara Yuda dan Dr.Wening juga membahas tentang pemilihan tempat dimana teror-teror bom dilakukan. Kita sama-sama tahu, pada awal tahun 2000an itu tempat-tempat publik seperti Kedutaan Besar, Hotel-hotel besar, sampai Gereja menjadi sasaran dari teror bom. Tentu pemilihan lokasi berbanding lurus dengan kelompok atau golongan masyarakat tertentu, dengan motif ideologis yang beragam pula. Dalam tahapan perbincangan ini, Dr.Wening pun mengaitkan bagaimana seolah-seolah semua skema yang didalihkan sebagai pemberantasan terorisme, mempunya konspirasi tersendiri yang kaitannya dengan sistem neokolonialisme dan kapitalisme negara-negara adidaya. Lantas negara seperti Indonesia, Malaysia, Filiphina yang dianggap sebagai negara bagian ketiga, menjadi lahan permainan dalam menggoreng isu-isu radikalisme semacam ini.
Strategi Pemilihan Teks, Neben-text dan Teks Berita
Yang menantang dalam menyusun kerangka lakon teater adalah model teks seperti apa saja yang hendak dimasukkan sebagai unsur penguat lakon. Pada lakon bagaimana kalau Munir saja?, saya menemukan dua unsur yang menarik dalam pemosisian tipe teks, yaitu tentang neben-text dan teks berita sebagai bagian dialog.
Penulis cukup lihai dalam menempatkan neben-text sebagai penguat dialog. Kehadiran dari beberapa neben-text seolah menjadi “helaan napas” untuk berhenti sejenak mencerna perdebatan yang terjadi antar karakter. Pada bagian tertentu, neben-text pada lakon bagaimana kalau Munir saja? Menyimpan sebuah makna tersirat, yang menegaskan beberapa value ideologis yang sedang disusun penulis di dalam lakon ini.
Mari kita lihat potongan dialog yang disertasi dengan sambungan neben-text :
103. YUDA: Boleh saya bertanya?
104. Dr. WENING : Silahkan.
105. YUDA : Ini di luar kebutuhan tesis ini.
106. Dr. WENING : Apa? Silahkan.
107. YUDA: Ibu setuju dengan gerakan terorisme, itu?
Dr. WENING terpana. Ia lemparkan pandangannya pada kejauhan. Seperti melamun.
108. Dr. WENING : Hanya Sartre yang setuju pada gerakan seperti itu: memasang bom, dan barangkali membunuh siapa saja, untuk menyatakan “tidak!”; Bukan Camus. Albert Camus.
109. YUDA : Ibu sendiri?
110. Dr. WENING : Jika aku tidak setuju pada pembunuhan para tersangka itu sebelum proses pengadilan, bagaimana aku setuju dengan pembunuhan yang lain? … … … Aku, juga tidak setuju hukuman mati.
YUDA tercenung. Matanya memandang tajam pada Dr. WENING. Dua mahasiswi melintas, mengenakan jilbab dengan warna anak muda yang cerah, dengan celana ketat yang mengukir lekuk tubuhnya yang sintal dan dadanya yang busung. Keduanya mengangguk hormat pada Dr. Wening. Lalu hilang di kejauhan.
Dr. WENING menenggak minumnya, mengunyah snack, matanya menerawang.
111. Dr. WENING : Ada banyak hal yang tak bisa kita jawab dan tak kita ketahui ujung-pangkalnya.
Jika kita baca ulang tumpukan baris dialog di atas, dan beberapa neben yang mendampinginya, bisa dibayangkan bahwa pada bagian tersebut semacam moment of truth dari motif Yuda yang sebenarnya, mengintrogasi Dr.Wening melalui posisinya sebagai dosen pembimbing. Pertanyaan Yuda terkait peng-iya-an atas paham gerakan terorisme kepada Dr.Wening, hanya dijawab Dr.Wening dengan lamunan.
Setelah lamunan itu, Dr.Wening mencoba menjawab pertanyaan Yuda secara tidak langsung, memutarnya dengan menyebut nama Satre dan Albert Camus. Yang menarik dari neben-text selanjutnya adalah, apa urgensi menghadirkan gambaran datangnya dua mahasiswi dengan penampilan macam tersebut (perempuan berjilbab dengan pakaian ketat)? Sebelum terburu-buru kebakaran jenggot atas tebakan stigmatisasi perempuan, saya justru menduga ada maksud eksplisit dari penghadiran neben-text tersebut. Bisa saja gambaran tentang dua mahasiswi tersebut menjadi peribahasa “dont judge book by the cover”, memanjangkan pemahaman tentang justifikasi pelaku terror yang sering mendapat stigma tertentu, khususnya di Indonesia.
Selanjutnya saya ingin membahas sedikit tentang penggunaan teks berita dalam lakon bagaimana kalau Munir saja?, yang cukup padat mengisi hampir 6 halaman jika diakumulasikan semuanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran teks berita utuh sebagai dialog menjadi data atau topik-topik yang jadi pembahasan pada tiap adegan. Tapi saya membayangkan bagaimana membacakannya sebagai dialog? Apakah teks berita tersebut dimaksudkan sebagai nomor-nomor monolog yang biasasnya ada dalam lakon teater? Atau justru hanya menjadi “properti”?
Munir, sebagai pertanyaan dan pernyataan lintas zaman
Pembahasan tentang Munir justru baru dibincangkan pada adegan 2, ketika Yuda bertemu dengan Marwan. Perbincangan off-record antara Yuda dan Dr.Wening tentang posisi “pelenyapan” Munir, diceritakan kembali ke Marwan yang mungkin memiliki peran sebagai “supervisor” Yuda dalam dunia intelnya. Munir adalah martir pertama yang harus dilenyapkan dalam upaya pembungkaman kasus pelanggaran HAM di Indonesia, baik di masa lalu, maupun yang mungkin akan terjadi di masa depan. Adegan 2 seperti sedang mempergunjingkan sosok Munir, jadi memang agak menyebalkan jika kita bayangkan kebenaran yang terjadi di balik konspirasi kejahatan HAM di Indonesia.
Munir bagaikan sebuah jembatan penghubung atas upaya pencarian keadilan di Indonesia. Sepak-terjangnya sebagai aktivis HAM, hingga mendirikan Kontras, patut dijadikan panutan bagaimana kegigihan sosoknya dalam mengungkap segala kejahatan kelam pemerintahan Orba. Namun seperti yang juga diceritakan dalam cerpen Aku Pembunuh Munir karya Seno Gumira Ajidarma, nasib Munir harus dibunuh dengan skenario arcun arsenik ketika dia terbang menuju Utrecht, Belanda, dalam proses tesisnya yang membahas topik tentang penghilangan paksa selama masa Orba.
Mungkin hipotesis tentang strategi pelenyapan Munir, untuk melanggengkan upaya pembungkaman kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu, juga menjadi contoh di masa depan bahwa pemerintah bisa berbuat sewenang-wenang kepada siapa saja yang berani mengkritik pemerintah, apalagi dalam konteks terorisme. Mari kita bayangkan jika Munir tidak terbunuh, dan upaya-nya memperjuangkan nasib-nasib korban penghilangan paksa pada zaman Orba, tentu akan menjadi rujukan para aktivis HAM untuk berjuang dan memiliki semangat yang serupa dengan Munir.
Tapi setidaknya, dalam lakon ini, entah dengan intensi apa yang dihadirkan Jasmine (istri Yuda) ketika menyarankan nama Munir sebagai salah satu opsi nama jabang bayi mereka, menjadi semacam secercah harapan, bahwa Munir-Munir yang lain akan terus lahir, semangatnya atas nama HAM tidak pernah mati.